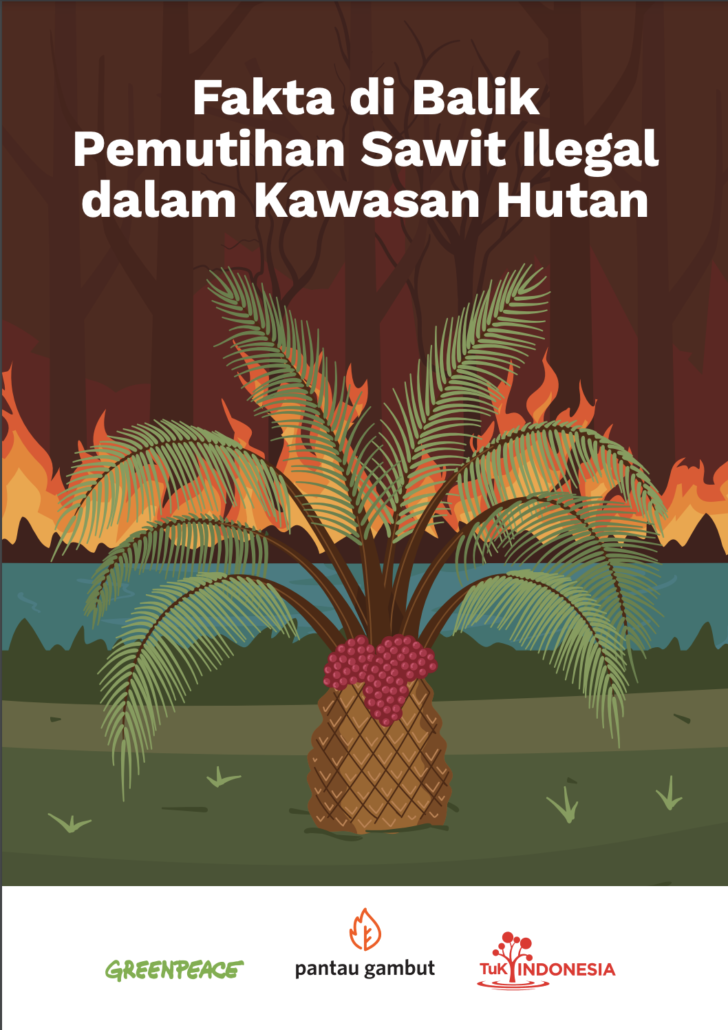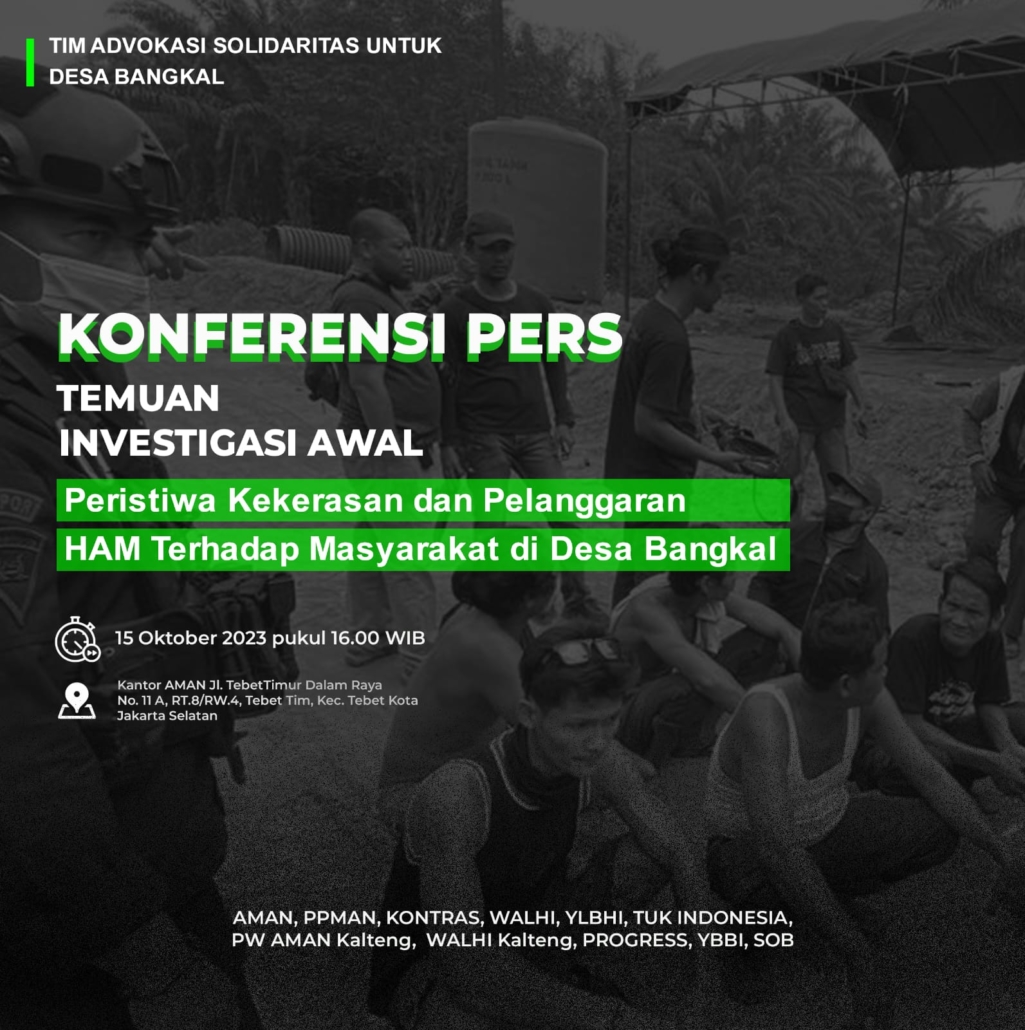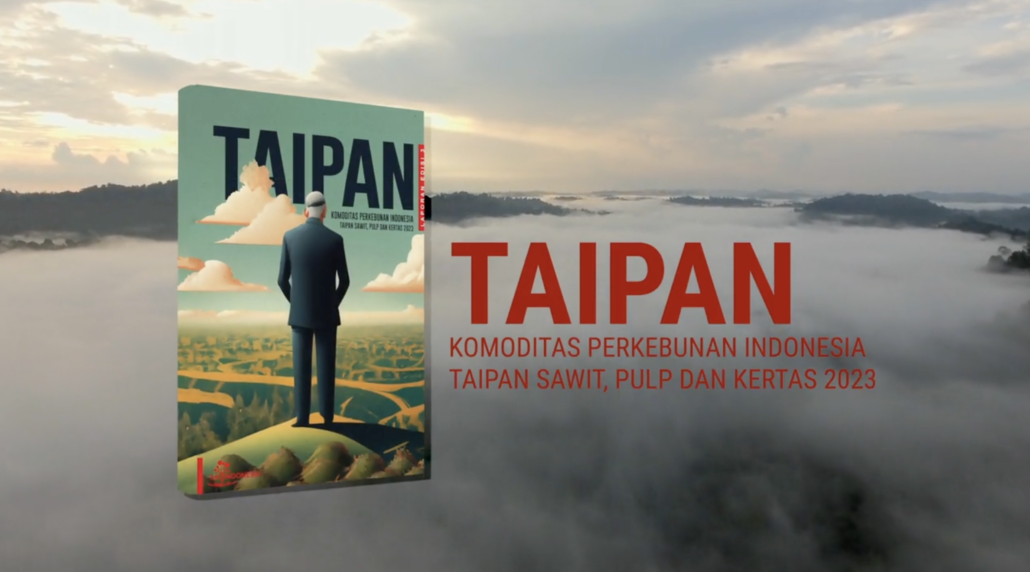Pemutihan Sawit Ilegal, Praktik Buruk Tata Kelola Sawit yang Memperparah Kejahatan Lingkungan
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” […]