
Diskusi Terbatas: Pendekatan Adaptif untuk Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa di Merauke, Papua
0 Comments
/
Kamis, 13 November 2014, Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta.
Keterlibatan…

Diskusi Terbatas: Pendekatan Adaptif untuk Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa di Merauke, Papua
Kamis, 13 November 2014, Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta.
Keterlibatan…

Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Pembiayaannya di Bengkulu, Sumatera.
Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Pembiayaannya yang kedua…
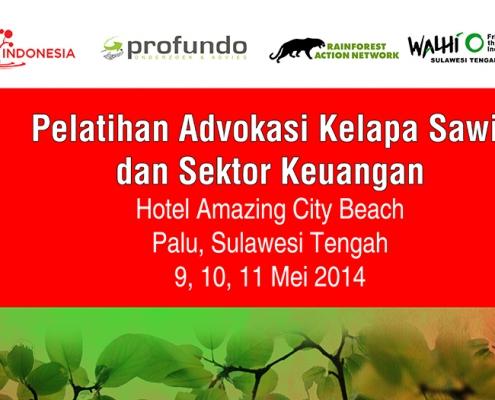
Pelatihan Advokasi Kelapa Sawit dan Pembiayaannya di Palu, Sulawesi Tengah.
TuK INDONESIA bersama-sama dengan Rainforest Action Network (RAN),…

Diskusi Terbatas: Wacana Keberlanjutan dan Substansi Persyaratan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Konteks Industri Kelapa Sawit (Putaran I)
Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011…

Workshop Internasional: HAM dan Agribisnis di Asia Tenggara
Montien Hotel Bangkok, 7-9 Agustus 2013. Ini merupakan pertemuan…

