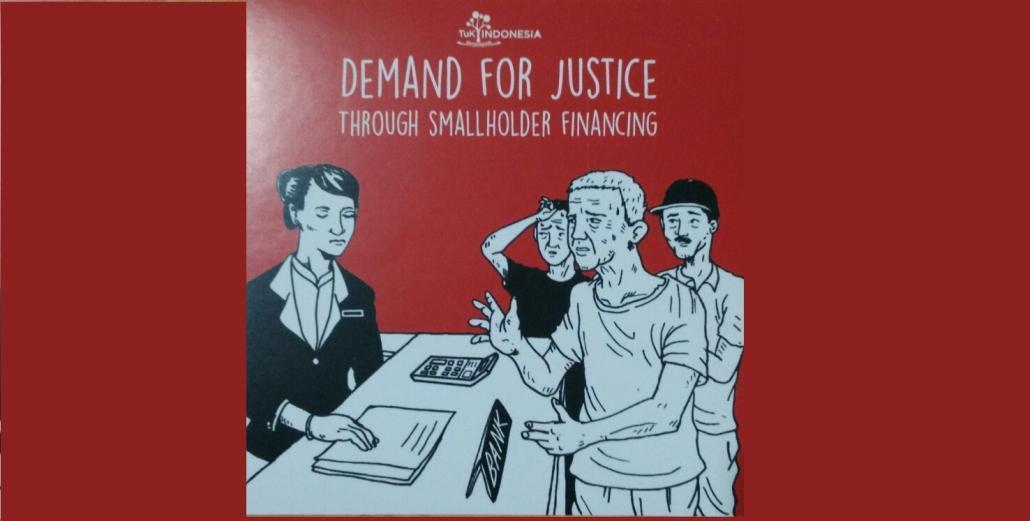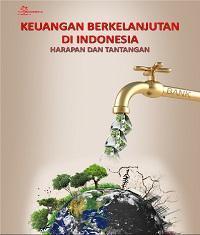Masyarakat Sipil Mengawal Pertemuan G20: Agar Perusahaan Bertanggung Jawab kepada Seluruh Pemangku Kepentingannya
Jalal Penasihat Keuangan Berkelanjutan Transformasi untuk Keadilan Indonesia Insentif dan Regulasi G20 adalah kumpulan pemerintahan, bukan kumpulan bisnis. Sehingga, […]